International Academy for Leadership
Dari Gummersbach untuk Indonesia: Strategi Baru Promosi HAM di Era Multipolar

Radhitya (kedua dari kanan bawah), bersama peserta IAF "Liberalism & Geopolitics: How To Deal With A Changing World Order".
Dunia saat ini sedang mengalami perubahan besar dalam cara negara-negara berinteraksi satu sama lain. Selama 30 tahun terakhir, nilai-nilai demokrasi dan kebebasan yang dijunjung tinggi oleh negara-negara Barat menjadi acuan utama dalam tata kelola global. Namun kini, muncul kekuatan-kekuatan baru seperti Tiongkok dan Rusia yang memiliki cara pandang berbeda tentang bagaimana negara harus dijalankan. Dalam situasi inilah, International Academy for Leadership (IAF) dari Friedrich Naumann Foundation mengadakan seminar dengan tema "Liberalism & Geopolitics: How To Deal With A Changing World Order" pada tanggal 7-14 September 2025 di Gummersbach, Jerman.
Seminar ini mengajukan pertanyaan penting: bagaimana nilai-nilai kebebasan, demokrasi, khususnya liberalisme dapat tetap relevan di tengah persaingan antar negara yang semakin ketat?. Yang membuat seminar ini istimewa adalah karena ini merupakan kegiatan internasional terakhir yang diadakan IAF setelah beroperasi selama 30 tahun. Meski demikian, seminar ini menjadi momen penting untuk merumuskan strategi baru dalam mempertahankan nilai-nilai liberalisme di tengah tantangan global yang semakin kompleks.
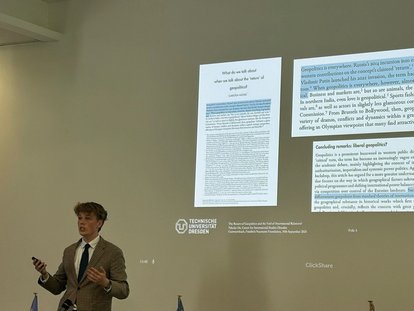
Rangkaian Kegiatan
Seminar selama delapan hari ini dirancang dengan cara yang menarik dan tidak membosankan. Dengan format "Building the Liberal World Order 3.0"—sebuah upaya kolektif untuk merumuskan bagaimana tata dunia yang lebih adil bisa dibangun di masa depan. Sebanyak 26 peserta dari 19 negara berbeda di Eropa, Asia, dan Afrika—termasuk saya sendiri dari Kementerian HAM Republik Indonesia—berkumpul untuk belajar bersama. Kami tidak hanya mendengarkan ceramah, tetapi juga terlibat langsung dalam berbagai kegiatan yang membuat kami merasakan bagaimana sulitnya mengambil keputusan di tingkat internasional. Kami dibagi dalam kelompok-kelompok kecil untuk membahas lima langkah strategis: mengidentifikasi masalah-masalah utama, merumuskan strategi, menyusun analisis per kawasan, menyeimbangkan pendekatan keras dan lunak, serta mengembangkan solusi terhadap fragmentasi ekonomi global.
Kegiatan dimulai dengan sambutan hangat dari Direktur IAF, Ibu Bettina Solinger, yang menjelaskan bahwa seminar ini adalah bagian dari perayaan 30 tahun IAF. Pada hari pertama, kami saling berkenalan melalui permainan yang menyenangkan sehingga suasana menjadi akrab meski baru bertemu. Hari kedua dan ketiga adalah momen paling menarik karena kami mengikuti simulasi sidang Majelis Umum PBB. Kami dibagi menjadi beberapa kelompok yang mewakili berbagai kawasan seperti Afrika, Uni Eropa, dan Amerika Serikat. Dalam simulasi ini, kami harus bernegosiasi dan mencari solusi atas konflik internasional yang dibuat semirip mungkin dengan kondisi nyata. Dr. Michael Rohschürmann dari Institute for Security Policy Kiel University yang memandu kegiatan ini membuat skenario yang sangat menantang. Dari sini saya belajar bahwa dalam dunia diplomasi, tidak ada yang hitam-putih—setiap keputusan melibatkan pertimbangan yang rumit antara kepentingan nasional dan nilai-nilai kemanusiaan.

Setelah simulasi, kami mendapat kesempatan mengunjungi kota Cologne untuk bersantai sambil tetap berdiskusi informal dengan peserta lain. Momen seperti ini penting karena membangun kedekatan personal yang membuat diskusi-diskusi selanjutnya lebih terbuka dan jujur. Hari-hari berikutnya diisi dengan paparan dari para ahli dan praktisi yang memiliki pengalaman langsung di lapangan. Setiap pagi dimulai dengan "Morning Check-in" di mana kami berbagi refleksi tentang apa yang sudah dipelajari hari sebelumnya. Metode ini sangat efektif karena membuat pembelajaran tidak hanya masuk ke kepala, tapi juga tertanam di hati.
Sesi yang paling seru adalah "Fight Club: Does the World Still Need the West?"—sebuah debat di mana kami harus mempertanyakan apakah negara-negara Barat masih berhak memimpin dalam urusan global. Debat ini membuka mata saya bahwa banyak negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin merasa tidak lagi ingin didikte oleh Barat, meskipun mereka menghargai nilai-nilai demokrasi.
Stefan Kolev, seorang profesor ekonomi, mengajak kami berpikir tentang masa depan perdagangan global. Apakah era globalisasi sudah berakhir? Apakah setiap negara akan kembali ke pola ekonomi yang lebih tertutup? Pertanyaan-pertanyaan ini sangat relevan dengan situasi Indonesia yang sangat bergantung pada perdagangan internasional. Seminar ditutup dengan sesi evaluasi dan pesta perpisahan yang dipimpin oleh Ibu Bettina Solinger. Beliau mengingatkan kami bahwa meskipun IAF ditutup, perjuangan untuk mempertahankan nilai-nilai kebebasan harus terus dilanjutkan.

Apa Yang Saya Dapatkan?
Seminar ini sangat relevan dengan pekerjaan saya di Kementerian HAM karena memberikan perspektif baru tentang bagaimana mempromosikan hak asasi manusia di dunia yang semakin kompleks. Selama ini, kita sering mendengar bahwa HAM adalah nilai universal yang harus dihormati semua negara. Namun dalam praktiknya, banyak negara menolak dengan alasan bahwa HAM adalah konsep Barat yang dipaksakan kepada mereka. Dari simulasi sidang PBB, saya belajar bahwa negara-negara besar sering kali harus memilih antara mempromosikan HAM atau menjaga hubungan baik dengan negara lain yang memiliki catatan HAM buruk. Misalnya, negara-negara Eropa yang mengkritik pelanggaran HAM di Arab Saudi, tapi tetap membeli minyak dari sana karena kebutuhan energi mereka. Ini adalah dilema yang tidak mudah dipecahkan.
Yang menarik, seminar ini mengajarkan bahwa pendekatan lama yang mengandalkan tekanan politik dan sanksi ekonomi tidak selalu efektif. Malah, pendekatan seperti itu sering membuat negara yang dikritik semakin menutup diri dan situasi HAM justru memburuk. Oleh karena itu, diperlukan strategi baru yang lebih halus—menggunakan diplomasi budaya, kerja sama ekonomi, dan dialog yang menghormati kedaulatan negara sambil tetap menegaskan pentingnya standar HAM minimum. Pembahasan tentang Belt and Road Initiative Tiongkok sangat menarik karena menunjukkan bahwa negara ini menawarkan bantuan pembangunan tanpa mengkritik praktik HAM negara penerima. Ini membuat banyak negara berkembang lebih memilih bekerja sama dengan Tiongkok daripada negara-negara Barat yang sering mengaitkan bantuan dengan perbaikan HAM. Bagi Indonesia, ini adalah pembelajaran penting: kita harus bisa menawarkan alternatif yang menarik—kerja sama yang menghormati kedaulatan tapi tetap mendorong perbaikan HAM secara bertahap.
Diskusi tentang perdagangan global juga membuka mata saya bahwa HAM tidak hanya soal kebebasan berbicara atau hak memilih dalam pemilu. Hak ekonomi, sosial, dan budaya—seperti hak atas pekerjaan, standar hidup layak, dan akses terhadap pendidikan—juga sangat penting. Ketika terjadi perang dagang atau sanksi ekonomi antar negara, yang paling menderita adalah rakyat biasa yang kehilangan pekerjaan atau tidak bisa membeli kebutuhan pokok. Oleh karena itu, promosi HAM harus mempertimbangkan dampak ekonomi dari setiap kebijakan.

Penjelasan tentang hybrid warfare—perang yang tidak hanya menggunakan senjata tapi juga serangan siber dan penyebaran berita bohong—sangat relevan dengan situasi saat ini. Di Indonesia, kita sering melihat bagaimana media sosial digunakan untuk menyebarkan kebencian dan memecah belah masyarakat. Ini adalah ancaman terhadap kebebasan berekspresi yang sehat karena membuat orang takut menyampaikan pendapat. Negara perlu melindungi warganya dari ancaman ini, tapi harus hati-hati agar tidak menjadi otoriter dengan mengawasi semua komunikasi warga.
Yang paling penting, seminar ini mengajarkan bahwa masa depan HAM bergantung pada kemampuan kita untuk menggabungkan idealisme dengan strategi yang realistis. Kita tidak bisa hanya berteriak tentang pentingnya HAM tanpa memahami konteks politik, ekonomi, dan budaya di masing-masing negara. Pendekatan jangka panjang yang fokus pada pendidikan, penguatan institusi lokal, dan pembangunan kapasitas lebih efektif daripada tekanan keras yang sering menimbulkan reaksi balik.
Menurut saya, pembelajaran dari seminar ini sangat berharga. Sebagai negara dengan lebih dari 300 kelompok etnis dan 6 agama resmi, Indonesia memiliki pengalaman unik dalam mengelola keragaman sambil menjaga kesatuan. Prinsip "Bhinneka Tunggal Ika" atau "berbeda-beda tapi tetap satu" bisa menjadi contoh bagi dunia bahwa menghormati HAM tidak berarti semua negara harus sama persis. Setiap negara bisa memiliki cara sendiri dalam menerapkan nilai-nilai universal HAM sesuai dengan konteks budaya mereka, asalkan prinsip-prinsip fundamental seperti larangan penyiksaan, kebebasan beragama, dan kesetaraan tetap dijunjung tinggi.

Perpisahan
Meskipun IAF harus berhenti beroperasi sementara setelah 30 tahun, semangat yang ditanamkan melalui seminar ini tidak akan mati. Malah, ini menjadi tantangan bagi institusi-institusi di negara berkembang seperti Indonesia untuk mengambil tongkat estafet. Kita bisa membuat program serupa yang melatih generasi muda pemimpin HAM yang lebih paham konteks lokal tapi tetap terhubung dengan jaringan global. Jaringan persahabatan yang terbangun selama seminar—dengan peserta dari Yunani, Bulgaria, Afrika Selatan, dan negara-negara lain—adalah aset berharga. Kami saling bertukar nomor kontak dan berjanji untuk tetap berhubungan. Di masa depan, jaringan ini bisa menjadi saluran kerja sama khususnya dalam isu-isu HAM regional dan global.
Kesimpulannya, seminar ini mengajarkan bahwa hak asasi manusia bukanlah sesuatu yang statis atau bisa dipaksakan begitu saja. HAM adalah nilai yang harus terus diperjuangkan, dinegosiasikan, dan disesuaikan dengan perubahan zaman. Tantangan terbesar bukan hanya menghadapi negara-negara otoriter, tapi juga bagaimana membuat konsep HAM relevan dan menarik bagi masyarakat biasa yang lebih peduli pada keamanan, kesejahteraan, dan martabat hidup mereka sehari-hari.
Dalam era ketidakpastian global ini, komitmen terhadap HAM memerlukan tidak hanya keberanian moral, tapi juga kebijaksanaan strategis. Kita harus pintar membangun aliansi, menyesuaikan metode advokasi, dan memastikan nilai-nilai kebebasan tetap relevan di tengah gelombang perubahan yang tidak bisa dihindari. Seminar IAF ini telah memberikan bekal yang sangat berharga untuk menghadapi tantangan tersebut.
Gummersbach, September 2025 – ein Kapitel schließt sich, doch die Lehren des IAF-Seminars bleiben. Für eine Welt, in der Freiheit und Menschenrechte weiterhin zählen.
Vielen Dank und auf Wiedersehen!

